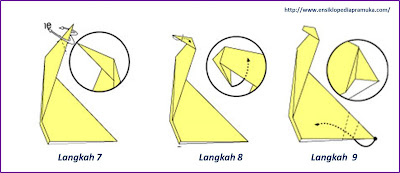Metode-metode Pengelolaan Konflik
- Stimulasi konflik, yaitu upaya menstimulasi konflik yang terlalu rendah sehingga pelaksanaan program menjadi lambat dengan agar menjadi konflik yang dapat memicu untuk persaingan untuk menuju ke hal-hal positip seperti percepatan kerja, pencapaian target yang lebih tinggi, memacu inovais dan kreativitas baru, dsb.
- Pengurangan atau penekanan konflik , yaitu upaya untuk mengurangi konflik yang terlalu tinggi sehingga berpotensi produktivitas, mengganggu kerjasama kelompok, terlantarnya pelaksanaan program, terganggunya emosi anggota kelompok, dsb.
- Penyelesaian konflik, yaitu upaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi agar tidak menganggu jalannya organisasi.
Metode Stimulasi Konflik
Konflik yang terlalu rendah dapat menyebabkan kehidupan organisasi menjadi pasif, kurang menantang, monoton sehingga menurunkan produktivtas, sikap inovatif dan motivasi meraih prestasi terbaik. Dalam menghadapi situasi semacam kehidupan organisasi perlu distimulasi agar dapat menumbuhkan konflik yang terukur. Metode stimulasi konflik meliputi :
- Memasukan atau penempatan orang baru atau orang luar ke dalam kelompok
- Penyusunan kembali strukur organisasi dan penempatan personal
- Penawaran bonus, penghargaan dan bentuk-bentuk apraisal lain untuk mendorong persaingan dan semangat kerja
- Pemilihan pemimpin kelompok baru yang tepat
- Perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan atau mengembangkan pola pikir dan pola kera "out of the box"
Metode Pengurangan Konflik
Pada sisi lain konflik yang terlalu tinggi sangat membahayakan kehidupan organisasi, oleh sebab itu perlu upaya "pendinginan suasana". Metode pengurangan konflik adalah metode mengelola tingkat konflik melalui “pendinginan suasana” tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Metode yang digunakan :
- Mengganti tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok
- Mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ‘ancaman’ atau ‘musuh’ yang sama
- Mempertemukan sisi-sisi persamaan dan mendialogkan sisi-sisi perbeadaan anggota kelompok untuk merumuskan konsensus-konsensus baru.
Metode Penyelesaian Konflik
- Metode dominasi dan penekanan, metode ini diterapkan dengan mengedepankan otoritas/kekuasaan dengan cara menerapkan kekerasan, penenangan, penghindaran atau aturan mayoritas - suara terbanyak adalah suara yang wajib diikuti.
- Metode kompromi, metode ini diterapkan dengan mengedepankan mencari sisi-sisi yang sama dan mendilogkan sisi-sisi yang berbeda melalui upaya pemisahan, arbitrasi, kembali ke peraturan-peraturan, menunjuk kelompok penengah, dsb.
- Metode pemecahan masalah secara integratif, metode ini diterapkan dengan mengedepankan pemecahan masalah yang telah memperhitungkan semua aspek terjadinya persoalan secara komprehensi melalui upaya konsensus (mencari titik temua), konfrontasi (mempertentangkan untuk menemukan kesamaan), penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi atau kepentingan yang lebih besar.
Mengenali Gaya dalam Mengeloa Konflik
Drs.H.Ahmad Thontowi, mensitir pendapat Johnson (Supratiknya, 1995) mengemukakan 5 gaya yang dapat dikenali untuk engelola konflik, yaitu :
- Gaya kura-kura : Seperti halnya kura-kura yang lebih senang menarik diri untuk bersembunyi di balik tempurungnya, maka begitulah orang yang mengalami konflik dan menyelesaikannya dengan cara menghindar dari pokok persoalan maupun dan orang-orang yang dapat menimbulkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih mudah menarik diri dari konflik, secara fisik maupun psikologis, daripada menghadapinya.
- Gaya ikan hiu : Menyelesaikan masalah dengan gaya ini adalah menaklukkan lawan dengan cara menerima solusi konflik yang ditawarkan. Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara satu pihak menang dan pihak lain kalah. MencaSpiritual kemenangan dengan cara menyerang, mengungguli, dan mengancam.
- Gaya kancil : Pada gaya ini, hubungannya sangat diutamakan dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi kerukunan.
- Gaya rubah : Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencaSpiritual tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting.
- Gaya burung hantu : Gaya ini sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadi sekaligus hubungannya dengan pihak lain, bagi orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk menyelesaikan konflik menganggap bahwa konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang bertikai.
Menyelesaikan Konflik
Banyak alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik, tergantung pada ruang lingkup, eskalasi, tipe dan tujuan organisasi serta personal-personal yang terlibat didalamnya. Kompetensi seorang pemimpin dan kesadaran para anggota organisasi untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi dan kelompok seringkali menjadi "pintu" penyelesain konflik yang lebih efektif
Pada bagian lain Drs.H.Ahmad Thontowi, mensitir pendapat Prijosaksono dan Sembel (2003) mengemukakan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang-kalah masing-masing pihak. Dalam sudut pandang ini terdapat empat kuadran manajemen konflik yaitu :
- Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi) : Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.
- Kuadran Menang-Kalah (Persaingan) : Kuadran kedua ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencaSpiritual kemenangan. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.
- Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi) : Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kalah-menang ini berarti ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya digunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak.
- Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik) : Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting.
Kode Kehormatan Pramuka sebagai Acuan Nilai Penyelesaian Konflik
Konflik memang tidak selamanya negatif karena ada juga konflik yang positip yang dapat mendinamisasikan kehidupan organisasi dalam mencapai tujuan. Konflik umumnya terjadi pada tataran "implementasi" atau "operasionalisasi" program dalam rangka mencapai tujuan organisasi, oleh sebab itu kembali ke "sistem nilai dasar" biasanya menjad pedoman resolusi konflik yang sangat efektif.
Kode Kehormatan Pramuka adalah sistem nilai yang bisa dijadikan salah satu pedoman dalam menyelesaikan konflik. Hal itu karena Kode Kehormatan Pramuka :
- merupakan budaya organisasi Gerakan Pramuka yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan berorganisasi.
- merupakan kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka, yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral, yang diterapkan bersama berbagai ketentuan lain yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab antar anggota serta pengambilan keputusan oleh anggota.
- merupakan landasan gerak bagi Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong;
Selamat Memandu. Salam Pramuka
Kepemimpinan Pramuka : Menejemen Konflik
Kode Kehormatan Pramuka
Sumber :
- Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS, dalam http://www.ipdn.ac.id/wakilrektor/wp-content/upu loads/MANAJEMEN-KONFLIK.pdf, diakses tanggal 18 Oktober 2013
- Drs.H.Ahmad Thontowi - Widyaiswara Madya Balai Diklat Kemenag Palembang, dalam http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/manajemenkonflik.pdf, diakses tanggal 18 Oktober 2013
- Arie Febrianto M, Jur. Tek. Industri Pertanian, FTP-UB, dalam ariefm.lecture.ub.ac.id/files/2013/05/9.-Manajemen-Konflik.ppt, diakses tanggal 18 Oktober 2013.